ENAM tahun silam, dunia dibawa masuk ke situasi mengkhawatirkan, menyaksikan konfrontasi baru antara Rusia dan Barat berkait dengan krisis Ukraina. Saat itu dirasakan, hubungan antara Rusia dan Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Barat lainnya, berada pada titik paling rendah sejak berakhirnya Perang Dingin tahun 1991.
Runtuh dan bubarnya Uni Soviet, pada Desember 1991 menandai berakhirnya Perang Dingin.
Perang Dingin, persaingan terbuka namun terbatas yang berkembang setelah PD II antara AS dan Uni Soviet serta sekutu mereka masing-masing. Perang Dingin dilancarkan di bidang politik, ekonomi, dan propaganda dan senjata secara terbatas. Istilah Perang Dingin, pertama kali, digunakan oleh penulis Inggris George Orwell.
Dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 1945, George Orwell memprediksikan akan terjadi kebuntuan nuklir antara “dua atau tiga negara super mengerikan, masing-masing memiliki senjata yang dapat digunakan jutaan orang untuk menjadi musnah dalam beberapa detik.”
Ketegangan antara Rusia dan Barat bereskalasi secara dramatis pada tahun 2014 setelah Moskwa melakukan intervensi militer atas Ukraina dan menganeksasi wilayah Crimea. Sebagai jawaban terhadap kebijakan Rusia itu, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Kondisi seperti itulah yang kemudian digambarkan sebagai Perang Dingin Baru.
Dari sudut pandang Moskwa, tindakan intervensi militer ke Ukraina dan aneksasi atas Crimea adalah sebagai jawaban terhadap kebijakan Barat “mencelupkan tangannya” (intervensi) ke dalam sphere of influence, wilayah pengaruh Rusia. Hal itu antara lain, perluasan keanggotan NATO, Uni Eropa dan promosi demokrasi ke negara-negara Eropa Timur yang sejak akhir PD II ada di bawah sphere of influence Rusia atau malah menjadi negara satelitnya.
Di tengah pandemi
Kini, situasinya berbeda. Perang Dingin Baru tidak lagi seperti di masa enam tahun lalu, seperti yang terjadi antara Barat (AS) dan Rusia. Dan, bukan lagi antara AS (Barat) dan Rusia, melainkan antara AS dan China. Kedua negara, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia, bersama-sama ingin menjadi yang paling unggul.
Maka itu sebagai buntutnya, terjadi persaingan strategis antara kedua negara.
Tahun lalu, Wakil Perdana Menteri Singapura yang juga Menteri Keuangan, Heng Swee Keat dalam sebuah pidatonya menggambarkan apa yang terjadi antara AS dan China.
“Ini adalah kompetisi strategis antara dua kekuatan utama —petahana dan yang baru muncul–untuk memperebutkan pengaruh dan kepemimpinan global.
Apa yang terjadi juga menggambarkan tentang perbedaan dalam sistem tata kelola dan bagaimana mengorganisasi masyarakat mereka, yang bersumber dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai mereka sendiri” (Yuen Foong Khong, 2020).
Dulu, ketika terjadi Perang Dingin antara AS (Barat) dan Uni Soviet, kedua kekuatan tersebut berusaha menunjukkan pada dunia sistem ekonomi dan pemerintahan mana yang lebih unggul, lebih superior.
Unjuk kekuatan itu tertangkap dalam perlombaan senjata, juga perlombaan di bidang luar angkasa—Soviet meluncurkan Sputnik, AS punya program Apollo—lalu krisis Rudal Kuba (peristiwa Teluk Babi), persaingan di Perang Korea, Perang Vietnam hingga krisis Yom Kippur 19973 saat terjadi Perang Arab-Israel.
Pada akhirnya, persaingan itu mencapai puncaknya ketika Uni Soviet bubar (1991). Ini berarti kemenangan di tangan AS. Perang Dingin berakhir. Francis Fukuyama malah menyebutnya sebagai “akhir sejarah.” Komunisme mati. Demokrasi liberal, menang.
Kini, di panggung ada dua kekuatan besar: AS dan China. AS sebagai incumbent adikuasa. Sementara China, sedang muncul sebagai adikuasa. Sudah barang tentu terjadi persaingan.
Sebagai kekuatan baru—terutama dalam bidang ekonomi—China tentu tidak ingin hanya menjadi nomor dua, duduk di belakang AS. China tentu ingin menjadi nomor satu. Mereka sudah membuktikan mampu memakmurkan rakyatnya yang lebih dari satu miliar jiwa.
Maka terjadilah persaingan strategis di antara mereka. Persaingan strategis itu beraneka ragam. Meskipun persaingan strategis itu berakar terutama pada upaya untuk keunggulan ekonomi dan penguasaan teknologi, namun memiliki komponen militer dan ideologis yang semakin penting.
Di tengah pandemi Covid-19 ini, persaingan mereka semakin kentara, semakin nyata.Tetapi pada akhirnya mungkin muncul pertanyaan mendasar: Negara mana yang memiliki konsep pengaruh yang lebih berkelanjutan?
Awal bulan ini, koran South China Morning Post (5/5), misalnya, memberitakan hubungan AS-China dalam beberapa hari terakhir telah mundur secara dramatis (setelah pandemi Covid-19). Hal tersebut telah meyakinkan para penasihat dan mantan penasihat pemerintah saat ini di kedua belah pihak bahwa hubungan bilateral telah jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade belakangan ini.

Menurut koran itu, pemerintah Donald Trump telah mengancam akan membatalkan perjanjian perdagangan fase satu. Perjanjian perdagangan fase pertama antara AS dan China adalah terutama melihat komitmen pembelian, liberalisasi pasar keuangan, pengurangan beban melalui regulasi produk pertanian, praktik nilai tukar, dan peningkatan perlindungan kekayaan intelektual seperti perlindungan rahasia dagang, hukuman sipil dan pidana.
Trump juga mengancam akan menaikkan tarif pada China, mendukung kontrol ekspor baru yang kuat terhadap perusahaan-perusahaan China hyang membeli produk teknologi AS. Dan, yang lebih “melukai hati” China adalah akan AS akan terus mendukung klaim-klaim bahwa Coronavirus (Covid-19) adalah buatan manusia dan bocor dari laboratorium di Wuhan, China.
Pada bulan Maret silam, misalnya, dalam suatu jumpa pers, Trump menyebut Covid-19 sebagai “Virus China.”
Ketika hal itu diprotes wartawan, Trump mengatakan, “Sebab virus berasal dari China. Ini sama sekali tidak rasis, tidak, tidak sama sekali. Virus dari China. Saya ingin akurat.”
Apa pun, alasan Trump, pernyataan seperti itu jelas mencerminkan adanya hal yang tidak beres dalam hubungan kedua negara. Apalagi Trump mengatakan, ia menggunakan istilah Virus China setelah media China menuduh bahwa tentara AS lah yang menyebarkan virus.
Pada bulan Maret lalu, China memerintahkan 13 wartawan dari The Wall Street Jorunal, The Washington Post, dan The New York Time untuk meninggalkan China. Tindakan itu disebutkanya sebagai lebih merupakan “tanggapan proporsional” terhadap tindakan pemerintah AS sebelumnya, yang membatasi media China.
Sikap Trump terhadap China sangat jelas. Dalam wawancara dengan Fox Businees Network, hari Kamis (14/5), Trump mengatakan, bahwa AS “dapat memutus seluruh hubungan” dengan China setelah pandemi. Sikap Trump itu didukung orang-orangnya, bahkan mereka bersikap lebih keras. Bahkan para senator dari Republik mendorong perlu dijatuhi sanksi dan disusun undang-undang baru untuk menghukum China karena dianggap menutup-nutupi kasus Covid-19 di awal mula. Sementara Kementerian Luar Negeri AS membatasi visa bagi para wartawan China yang bertugas di AS.
Apakah berhenti sampai di sini saja atau akan bertambah buruk hubungan kedua negara?
Zaman Baru?
Apa yang terjadi akhir-akhirnya, sebagai kelanjutan dari perang dagang, menggambarkan bahwa AS dan China benar-benar ada dalam era Perang Dingin Baru. Tentu, Perang Dingin baru antara AS dan China ini berbeda dengan Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet dulu.
Perang Dingin baru antara AS dan Cina menampilkan persaingan penuh dan decoupling yang cepat. Hubungan AS-Cina tidak lagi sama dengan beberapa tahun yang lalu, bahkan tidak sama dengan beberapa bulan yang lalu.
Meski sepertinya ada usaha untuk tidak terjadi Perang Dingin baru, tetapi rasanya angin geopolitik bertiup ke arah sana, Perang Dingin baru. Hal itu, antara lain terjadi karena retorika-retorika AS, pemimpin AS yang oleh banyak kalangan dinilai buruk, yang memanaskan situasi.
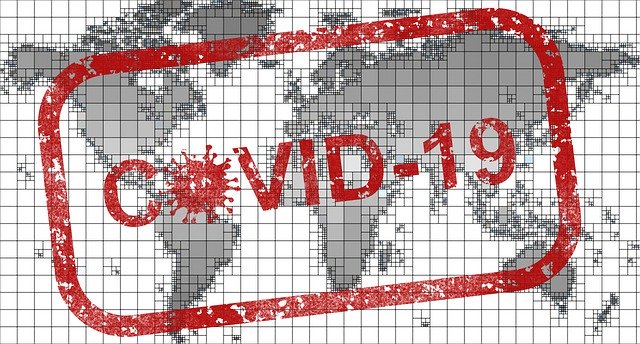
AS yang kini semakin “keteteran” menghadapi China menganggap bahwa China adalah ancaman terhadap kekuatan ekonomi dan keamanannya.
Meskipun harus diakui bahwa sekarang ini—setelah terjadi pandemi Covid-19—China benar-benar telah muncul sebagai “lebih unggul” dibandingkan AS. China, bahkan, lebih dipandang oleh negara-negara sekutu AS di Eropa dibanding AS sendiri.
Kita melihat bahwa persaingan strategik akan tetap mendominasi antara keduanya ke depan. Apakah pandemi Covid-19 ini benar-benar akan mengawali terbitnya zaman baru yakni Perang Dingin baru antara AS dan China seperti yang terjadi di kala terjadi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet di masa lalu?
Dan, pertanyaan akhirnya adalah, apakah persaingan itu akan mengarah pada persaingan permanen dan permusuhan habis-habisan atau sementara saja?
Kita tunggu babak ini berlanjut untuk menemui titik akhir, sambil berharap bahwa hubungan keduanya membaik kembali sehingga memberikan lingkungan yang mendukung bagi terciptanya perdamaian di kawasan.








































