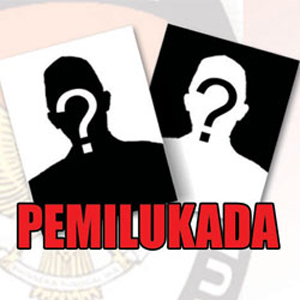HARI Selasa tanggal 25 Juli 2017 kemarin telah berlangsung acara tahbisan imam diosesan (praja) KAS di Kapel Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan, Yogyakarta.
Hari ini, marilah kita simak perjalanan sejarah panggilan mereka masing-masing.
Unik dan menarik.
Berikut ini adalah kisah-kisah mereka sebagaimana materinya dikirim ke Redaksi oleh Rektor Seminari Tinggi St. Paulus di Kentungan, Yogyakarta: Romo Yoseph Kristanto Suratman Pr. Awal Agustus 2017 ini, Romo Kristanto siap mengemban tugas baru di lingkungan KWI sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Seminari.
Redaksi Sesawi.Net mengucapkan terima kasih kepada Tim Panitia Tahbisan Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan yang melalui Romo Rektor sudah berbagai bahan cerita sejarah panggilan dari masing-masing neomis ini.
————
Romo Emmanuel Graha Lisanta Pr: Ikutlah Aku
PERJALANAN panggilan imamat saya bermula dari sebuah pengalaman yang sederhana: pengalaman kebingungan setelah lulus SMA. Sudah menjadi kebiasaan di sekolah saya, menjelang akhir kelas XI, setiap siswa akan ditanyai oleh guru BK tentang rencana studi lanjut setelah lulus SMA.
Saat itu saya sudah menjawab akan kuliah di STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Meskipun demikian, saya masih ragu. Dalam keraguan itulah, saya sering mampir ke gereja sepulang sekolah. Setelah nggalau dan berdoa sejenak, barulah saya pulang ke rumah. Suatu kali saya menyempatkan diri untuk mengikuti Ekaristi Sabtu sore. Saya sengaja datang lebih awal agar bisa berdoa pribadi terlebih dahulu.
Tiba-tiba saat saya sedang memandangi wajah Yesus yang ada di salib besar yang tergantung di belakang altar, saya seolah melihat Yesus menoleh ke arah saya dan ada suara, “Ikutlah Aku!” Saya kaget. Ada perasaan takut, bingung, sekaligus takjub. Mana mungkin patung Yesus itu bisa bergerak dan berkata-kata? Saya kembali kaget ketika dalam Ekaristi sore itu dibacakan kisah tentang Yesus yang memanggil Matius si pemungut cukai untuk menjadi murid-Nya.
Di sana saya menemukan kata-kata Yesus: “Ikutlah Aku!” (Mat 9:9). Spontan muncul pertanyaan, “apakah Tuhan memanggil saya untuk menjadi imam?”
Pertanyaan itu membawa saya kembali ke masa lalu.
Dulu, ketika masa-masa awal bersekolah di TK, bapak mengajari saya: “Le, yen didangu Bu Guru sesuk gedhe arep dadi apa, matur wae, dados romo, Bu!” (Nak, kalau ditanya Ibu Guru besok saat dewasa mau jadi apa, jawab saja, jadi romo, Bu!”). Tentu saja, saat itu saya tidak tahu persis apa arti romo atau imam. Seiring perjalanan waktu, saya semakin mengerti dan mengenal apa dan siapa imam itu. Saya bahkan memiliki kekaguman pada imam karena kebaikan hatinya, keramahannya, kepandaiannya dalam banyak hal, serta kewibawaannya.
Pernah, saking kagumnya, dalam lomba menggambar yang diselenggarakan oleh panitia HUT paroki, saya mengabaikan ketentuan lomba. Bukannya menggambar Yesus sesuai ketentuan lomba, saya justru menggambar romo paroki yang berpesta bersama umat. Anehnya, saya justru menjadi juara I dalam lomba menggambar itu. Ketika SMP, saya pun pernah mendapat julukan “romo” karena dinilai alim dan selalu mendapat nilai yang tinggi dalam pelajaran agama Katolik. Namun saat itu saya tidak pernah berkeinginan menjadi imam. Barulah saat ada salah satu temanku yang diterima di Seminari Menengah Mertoyudan, saya mulai berpikir untuk menjadi imam.
Namun karena penasaran bagaimana rasanya bersekolah di SMA, saya pun lebih memilih melanjutkan sekolah ke SMA dan tidak pernah lagi memikirkan cita-cita sebagai imam. Lha kok persis saat saya sedang memantapkan pilihan untuk melanjutkan kuliah di STAN, muncul pertanyaan: apakah Tuhan memanggil saya untuk menjadi imam? Apakah saya harus meninggalkan semua itu dan menjadi seperti Matius? Apakah Tuhan memanggil saya sudah sejak dulu?
Saya merasa tidak yakin bisa menjadi imam. Saya bukanlah orang yang aktif dalam kegiatan menggereja, bahkan untuk sekadar menjadi anggota putra altar. Selain itu saya pun termasuk anak yang clingus (pemalu) dan mudah merasa minder. Anehnya, semakin saya menghindar dan menolak ajakan Yesus itu, saya semakin merasa tidak nyaman dengan diri saya sendiri, dengan orang-orang di sekitar saya, dan dengan Tuhan.
Akhirnya, saya pun memberanikan diri untuk menceritakan hal ini kepada keluarga. Keluarga saya sama sekali tidak keberatan seandainya saya menjadi imam. Mereka hanya berpesan agar saya bersungguh-sungguh dan konsekuen dengan setiap pilihan yang saya buat ini. Merasa mantap, saya pun menceritakannya kepada romo paroki, guru, dan teman-teman saya. Semuanya mendukung saya. Jadilah, saya memulai babak baru dalam hidup saya. Di sela waktu persiapan ujian akhir SMA, saya mendaftar ke Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan dan mengikuti serangkaian tes. Tidak lama kemudian saya dinyatakan iterima sebagai seminaris KPA.
Di Seminari Mertoyudan, saya hidup bersama dengan sesama remaja laki-laki yang juga ingin menjadi imam. Awalnya, saya sering merasa minder dan canggung karena merasa kalah pengalaman hidup berasrama dan kalah pengetahuan tentang panggilan sebagai imam. Syukur, teman-teman baru saya ini sangat baik. Mereka membantu saya untuk cepat beradaptasi melalui sapaan, ejekan, sharing, kerja, dan sesekali berbuat kenakalan bersama.
Pernah suatu kali, saya dipanggil romo pamong dan diberi sebuah tugas khusus. Saya diminta untuk belajar nakal. Tugas yang aneh, karena biasanya orang diminta belajar berbuat baik dan tidak nakal. Mungkin saat itu saya dinilai terlalu alim dan masih sulit berbaur dengan teman-teman, maka saya pun diberi tugas itu. Dengan penuh semangat dan sukacita, teman-teman membantu saya. Mereka mengajari saya untuk datang terlambat ke kapel, memetik alpukat, memasak mie saat jam studi, dan aneka kenakalan khas seminaris lainnya.
Anehnya, sekalipun saya melakukannya sebagai tugas, tetap saja saya mendapat hukuman atas kenakalan yang saya lakukan. Di seminari menengah inilah saya belajar hidup bersama dalam sebuah komunitas, belajar menjadi remaja “normal” yang kadang berbuat nakal dan salah, serta belajar menanggapi panggilan Tuhan dengan segala keunikan pribadi.
Perjalanan panggilan saya berlanjut di Seminari Tahun Orientasi Rohani Sanjaya Jangli. Bersama 19 teman lainnya, saya mengolah panggilan sebagai calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Motivasi saya menjadi calon imam disosesan (praja) Keuskupan Agung Semarang saat itu adalah ingin menyumbangkan sesuatu yang saya punya untuk Gereja keuskupan, yang selama ini sudah menjadi rumah saya dan sungguh mencintai saya.
Di hari pertama, saya sudah mendapat teguran dari staf seminari. Ceritanya, beberapa minggu sebelum masuk ke Jangli, saya harus menjalani opame karena demam berdarah. Tanpa sepengetahuan saya dan kelurga, perawat rumah sakit menuliskan “Frater” di depan nama saya. Padahal saat itu saya belum resmi menjadi frater.
Tentu saja informasi tentang adanya frater Jangli yang opname di rumah sakit ini telah membuat staff seminari kebingungan. Akhirnya, saya pun harus mengklarifikasi hal ini dan meminta maaf. Di Jangli inilah saya secara khusus belajar untuk semakin memperdalam hidup doa.
Pernah suatu kali saya dan teman-teman diajak bermeditasi di bawah terik matahari. Sejam kemudian, saat bersharing tentang pengalaman doa, kami justru asyik mengamati kulit kami yang belang dan menikmati bau gosong matahari. Di Jangli ini jugalah, saya belajar mengelola rumah dan berpastoral mendampingi anak-anak di pinggiran kota Semarang.
Setahun kemudian, saya melanjutkan formatio di Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan. Di sinilah saya menjalani hari-hari untuk belajar filsafat dan teologi sambil terus mengolah hidup doa, pastoral, dan komunitas. Banyak pengalaman yang mencerahkan saat mempelajari pemikiran para filsuf dan teolog. Saya terbantu untuk semakin mengenal diri, Tuhan, dan sesama, serta semakin meneguhkan panggilan saya.
Demikian juga saat berdinamika bersama teman-teman sekomunitas dan berjumpa dengan umat. Saya terbantu untuk semakin menghayati hidup sebagai orang yang terpanggil, yang juga ikut bertanggungjawab menjaga panggilan orang lain.
Ada kalanya hidup dalam rutinitas semacam itu terasa berat dan membosankan. Justru dalam situasi itulah ketahanan dan keteguhan diri ditempa. Syukur saya tidak pernah kehabisan cara untuk sekadar berefreshing, misalnya dengan mengunjungi keluarga, melakukan hobi menggambar dan berkebun, duduk mengobrol dan makan bersama teman, jalan-jalan di sekitar seminari, atau sekadar selonjor di gazebo kebun belakang seminari.
Di seminari ini saya sungguh mengalami ditumbuhkembangkan dalam panggilan imamat. Pengalaman inilah yang coba saya bagikan saat menjalani Tahun Orientasi Pastoral (TOP) di Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan. Menjadi “kakak” sekaligus teman seperjalanan bagi 82 seminaris di Medan Tamtama (kelas X) bukanlah hal yang mudah.
Selain diajak untuk bersabar menghadapi perbedaan karakter remaja zaman sekarang, saya pun diajak untuk semakin menghargai panggilan imamat. Para seminaris menunjukkan kepada saya bahwa dibutuhkan perjuangan untuk bertahan dalam pilihan mengikuti Yesus di jalan panggilan imamat. Hal ini semakin memantapkan perjalanan saya di Seminari Tinggi St. Paulus Kentungan hingga saat ini.
Di dalam proses pendidikan sebagai calon imam inilah saya belajar banyak hal. Saya belajar bahwa jawaban “ya” atas panggilan Tuhan itu membawa saya ke tempat dan situasi yang berbeda-beda dan seringkali sungguh-sungguh baru: tugas-tugas studi dan pastoral, perjumpaan dengan aneka macam orang, serta pengalaman jatuh-bangun hidup dalam rutinitas seminari. Saya seolah dibawa ke tempat-tempat baru kapan pun dan di mana pun Ia berada.
Saya pun belajar bahwa jawaban “ya” atas panggilan Tuhan itu harus selalu disegarkan terus-menerus. Jawaban itu bukanlah jawaban sekali untuk selamanya. Ada banyak godaan dan tantangan untuk bertahan dalam jawaban itu dan karena itulah perlu keberanian untuk jujur dan disiplin pada diri sendiri, Tuhan, dan pembimbing. Di sinilah saya semakin yakin bahwa panggilan menjadi imam adalah sungguh rahmat Tuhan sekaligus hasil perjuangan manusia untuk berani menanggapi rahmat itu.
Saya juga belajar bahwa Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu mulus dan terang bagi saya, tetapi Ia berjanji akan selalu ada bersama saya. Tuhan tahu betapa lemah dan rapuhnya saya, tetapi Ia memilih saya. Ia pun selalu menyertai dan memampukan saya untuk bertahan. Saya belajar di dalam kelemahan dan kerapuhan manusiawi itu, Tuhan selalu berkarya.“Harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.” (2 Kor 4:7).
Nasihat St. Paulus inilah yang menjadi penyemangat saya dalam menapaki jalan panggilan dan perutusan ini. Syukur atas semua pengalaman yang membawa saya sampai di sini. Terima kasih kepada bapak, ibu, mbak, adik-adik, saudara-saudari, staff dan karyawan seminari, donatur, umat, dan semua saja yang mendukung saya dengan caranya masing-masing.
Berkah Dalem. (Berlanjut)