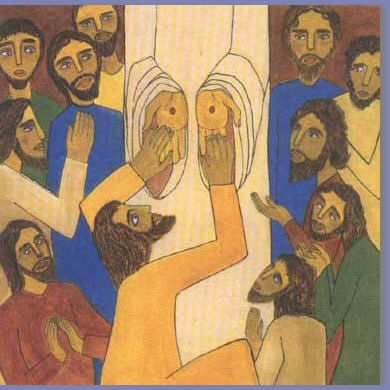RASANYA belum terlalu lama, 11 Mei 2020, saya menulis status di Facebook tentang para Uskup Jesuit yang purnakarya, Kardinal Julius Riyadi Darmaatmadja SJ dan Mgr. Julianus Sunarka SJ.
Dua-duanya cukup saya kenal, terlebih saat 14 tahun terakhir ini berkarya di dua tempat dalam lingkungan KWI.
Pertama, Rama Kardinal Sepuh. Saya mencecap sedikit kedalaman spiritualitas Rama Kardinal Julius Riyadi Darmaatmadja SJ saat turut menyiapkan biografi beliau tahun 2012-2014, yang terbit untuk memperingati usianya ke-80.
Mendengarkan sharing tentang perjalanan hidupnya sejak kecil di tengah keluarga, lahir 20 Des 1934 di Jagang, Salam, Magelang, Jawa Tengah. Masa pembentukan karakter di seminari sampai menapaki perjalanan hidup spiritualnya sebagai pelayan Gereja Katolik yang setia dalam kebersahajaan yang melekat kuat dalam dirinya.
Masa keprimatannya sebagai Kardinal, sebagai salah seorang “Pangeran Gereja” yang diangkat secara khusus oleh Sri Paus saat ia menjadi Uskup Agung Semarang (26 Nov 1994); dipindah ke Jakarta menjadi Uskup Agung Jakarta pada Januari 1996, sampai purnakarya pada 28 Juni 2010, lalu memilih kembali ke Girisonta untuk mengisi hari-harinya sebagai pendoa di komunitas Wisma Emaus.

Monsinyur Sunarka punya “mata elang”
Mgr. Julianus Kemo Sunarka SJ saya kenal sejak saya ditunjuk menjadi Direktur OBOR (Januari 2007 sampai Desember 2015), saat ia menjadi Wakil Ketua Perkumpulan Rohani OBOR (PRO), lembaga para uskup yang mengayomi karya pastoral melalui Penerbit OBOR & Toko Rohani OBOR.
Konon ia sendiri yang “berburu” mencari calon direktur, setelah para uskup sepakat menyerahkan pelayanan OBOR kembali kepada imam, sebuah keputusan yang menimbulkan pro-kontra di kalangan internal OBOR maupun di kalangan umat Katolik lainnya waktu itu.
Empat tahun pertama menjadi Direktur OBOR, saya sungguh dikawal oleh para pengurus PRO, agar benar-benar bisa bekerja dengan tenang merapikan yang belum rapi, meluruskan yang belum lurus, dan membesarkan yang masih terlalu kecil, agar keberadaan OBOR sebagai sebuah lembaga pelayanan para uskup semakin dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak.
Dawet Ireng adalah buku tentang serba-serbi Mgr J. Sunarka SJ yang ditulis oleh Sutriyono Robert memperlihatkan karakter Uskup Purwokerto yang merakyat, guyonan dipakainya untuk membangun relasi antarpribadi
Sebulan sekali dengan kereta api ditempuhnya perjalanan Purwokerto-Jakarta, pulang pergi, hanya untuk rapat bersama 3-4 jam saja.
Perjalanan ini menggambarkan semangat pengorbanan luar biasa demi “tanggung jawab tambahan” yang dibebankan ke pundaknya oleh para uskup lainnya.
Dua keutamaan amat menonjol dalam pribadinya sebagai petinggi OBOR adalah keberpihakan pada kepentingan banyak orang dan ketajamannya menganalisis angka-angka. “…kalau OBOR-nya sampai bubar, berapa banyak orang yang akan kehilangan nafkah”, begitu dikatakannya dalam berbagai kesempatan.
Hak atas profit sharing bagi karyawan OBOR adalah ide yang muncul dari Mgr. Sunarka, kemudian disetujui oleh para Pengurus PRO.
Ia bangga, karena bersama partner-nya, Mgr. Agustinus Agus (Ketua PRO), bisa membuat OBOR kembali diperhatikan keberadaannya oleh para uskup, yang pada mulanya ingin membubarkan lembaga ini.
OBOR yang baik telah menghadirkan peranan para uskup dalam pelayanannya bagi kebutuhan Umat Katolik. Karyawan dan keluarganya terjamin hidupnya dengan penghasilan yang baik. Para penyelia (supplier) bisa menghidupi para karyawannya juga. Itu dampak-ganda (multiplier effect) atas kehadiran OBOR yang dipertahankan keberadaannya dan dirawat baik.
Dirawat di rumah sakit menjelang terbitnya Dawet Ireng.

Meskipun telah 4,5 tahun pensiun sebagai Direktur OBOR, rasanya saya masih hafal gaya bicara, ide-ide pemikiran, guyonan, dan segala kebiasaannya saat kumpul bersama untuk rapat PRO, evaluasi tahunan, rekoleksi bersama, dan sebagainya.
Simbah selalu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Kalau toh ada kekurangan, pasti ada trik yang pas baginya untuk menyampaikan correctio fraternal bukan mencela, apalagi mencerca.
Baginya, tiap orang itu unik karena diciptakan oleh Sang Agung yang tak pernah salah. Kalau ada yang melenceng, jangan dimusuhi tapi diberi kesempatan memperbaiki, caranya mungkin dikursuskan lagi, disekolahkan lagi, dan sebagainya, supaya dia menjadi baik.
“Jadi orang itu harus mampu menjaga dirinya, menjaga tingkah lakunya, menjaga “ini, ini, dan…. iniiiiii,” katanya sambal dengan tangan gemetar (tremor, gejala parkinson) menunjuk dahi, dada, dan selangkangan (maaf).
Itu nasihatnya kepada banyak orang, terutama kepada para rama, apalagi rama-rama muda, dengan gaya bicara dan mimik yang khas, membuat orang yang dinasihatinya tertawa tak merasa disentil.

Di lain waktu, saat tahu ada romo yang akan ditugaskan di lingkungan KWI, maka tanpa diminta, Mgr. Narko menggoyang-goyangkan jarinya di meja lalu berkata, “Nah kalau yang ini begini-begitu, nanti usahakan supaya begini-begitu yah, supaya aman”.
Simbah memang mempunyai kemampuan indera keenam, yang dalam psikologi disebut extrasensory perception (ESP), kemampuan seseorang menerima informasi yang tidak diperoleh melalui kelima indera fisiknya namun dirasakannya dengan pikiran.
Tidak mengherankan kalau oleh banyak pihak ia diminta membantu mencarikan titik mata air.
Sang Dukun Banyu yang banyak membantu menemukan mata air dan selalu menasihati rekan-rekan muda untuk pandai menjaga diri, “ini, ini, dan iniiiiii.”
Ketika ada uskup lain yang mencandainya karena nama kecilnya ‘Kemo’, ah mungkin kependekan dari ‘kemoterapi’, dengan santai ia menjelaskan, “Saya ini orang kampung; karena lahir pada hari Kamis, yah dinamai Kemo…”
Sebuah jawaban sederhana dan membumi dari pribadi yang amat bersahaja.
Ia dilahirkan pada 25 Des 1941 di Minggir, Sleman, Yogyakarta. Ditahbiskan sebagai imam oleh Kardinal Justinus Darmojuwono pada tanggal 3 Desember 1975. Dikonsekrasi menjadi Uskup Purwokerto oleh Kardinal Julius Riyadi Darmaatmadja SJ pada tanggal 8 September 2000 sampai memasuki purnakarya pada 29 Desember 2016, lalu kembali ke Girisonta mengisi hari-harinya.
Pada usia 78,5 tahun, Jumat 26 Juni 2020, ia meninggal dunia di RS St. Elisabeth, Semarang. Jenazahnya dimakamkan sehari kemudian di Taman Makam Maria Ratu Damai, tempat pemakaman para Yesuit di komplek Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah.
Menjadi resi dalam keheningan Girisonta
Merpati tak Pernah Ingkar Janji, judul novel lawas karya Mira W yang terbit sekian puluh tahun lalu.
Mengapa merpati? Karena kesetiaannya menjadi inspirasi kehidupan banyak orang. Setelah terbang mengelana sehari penuh ia pasti akan kembali ke sangkarnya.

Begitu juga konon para Yesuit yang sejati. Mereka mengawali hidup dan penghayatan spiritualitasnya di Girisonta, menempa dan mengolah batinnya sedemikian rupa di sini agar kelak bisa menghidupi raganya.
Setelah itu ia akan mengelana sepanjang hari-hari hidupnya sampai ke ujung-ujung bumi sesuai perutusan yang diterimanya.
Pada akhirnya, Girisonta juga yang akan menjadi pelabuhan hari tuanya, tempat di mana ia akan kembali bertapa sebagai seorang resi yang matang akan makna hidup.
Situasi sudah berbeda jauh, “…kini ia bukan lagi ulat yang merayap di dahan pohon yang dengan gigi-gigi tajamnya menghabiskan dedaunan sesukanya, namun telah menjadi kupu-kupu yang bisa terbang tinggi membawa raganya ke mana pun dalam hidupnya yang paripurna…”
Ketika orang bisa berpasrah kepada Sang Pemilik Kehidupan, ia akan lepas bebas dari jeratan ragawi yang fana dan terkungkung dalam dimensi ruang dan waktu.
Selamat jalan, Monsinyur Sunarka.
Jakarta, 27 Juni 2020
Agust Surianto Himawan
Ref: https://www.membumikanide.com