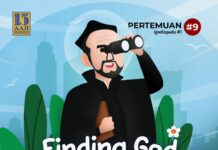[media-credit name=”Google.fr” align=”alignnone” width=”150″] [/media-credit]BILA kita merunut gambaran Allah menurut Ignatius ini secara sungguh-sungguh, maka kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan yang merupakan tantangan bagi hidup kita.
[/media-credit]BILA kita merunut gambaran Allah menurut Ignatius ini secara sungguh-sungguh, maka kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan yang merupakan tantangan bagi hidup kita.
(1) Dimensi personal
Pada level ini, kita ditantang untuk bertanya apakah gambaran Allah yang kita punyai sudah menyerupai gambaran Allah yang dimiliki oleh Ignatius setelah “pembebasan”-nya. Ataukah, gambaran tersebut masih seperti gambaran yang dia alami sebelum ia dilepaskan dari litani skrupelnya. Kalau gambaran Allah yang kita miliki ternyata masih salah, kita diundang untuk mengoreksinya. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari akar-akarnya untuk kemudian membereskannya.
Dari pengalaman saya pribadi maupun pengalaman cukup banyak orang yang sempat diceritakan kepada saya, nampak jelas bahwa gambaran diri yang saya miliki dan gambaran mengenai Allah yang saya miliki itu ternyata saling mempengaruhi. Hal ini juga diperkuat oleh analisis beberapa ahli.
Kkalau gambaran diri yang kita miliki itu negatif, ada kemungkinan besar bahwa gambaran Allah yang kita miliki itupun juga negatif. Demikian pula kalau gambaran Allah yang kita miliki itu negatif, tidak jarang kita juga akan bersikap negatif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.
Pengalaman traumatik
Gambaran negatif mengenai diri sendiri seringkali disebabkan oleh beberapa pengalaman traumatik dalam hidup kita, entah karena perlakuan orang-tua, pendidik, ataupun figur otoritas lainnya. Ppengalaman-pengalaman traumatik seperti ini dapat disembuhkan antara lain dengan menceritakannya kepada orang-orang yang kita percayai. Namun ada kalanya kita perlu menjalani suatu terapi.
Bersamaan dengan itu, kita perlu memohon kepada Allah, agar ia berkenan mengoreksi gambaran diri yang salah tersebut. Dengan dibetulkannya gambaran diri yang salah itu, pelan-pelan gambaran mengenai Allah yang salah juga akan disembuhkan. Dan kita akan mampu menerima Allah apa adanya!
Berkaitan dengan hal ini, sebagai orang yang dalam batas-batas tertentu mempunyai “otoritas” atas kehidupan orang lain, kita diingatkan agar sikap, kata-kata maupun tidakan kita jangan sampai “melukai” hidup orang-orang yang diserahkan oleh Tuhan kepada kita.
(2) Dimensi struktural
Ada kesulitan lain yang mendasar untuk memahami Allah seperti yang diwartakan oleh Kitab Suci dan yang diimani oleh Ignatius setelah pengalaman di Manresa. Kesulitan itu muncul dari struktur masyarakat dan gereja yang didominasi oleh sistem dan struktur patriarkal.
Sistem dan struktur seperti ini terlalu mengagungkan nilai-nilai dominasi, subordinasi, manipulasi, kontrol, rationalisme, serta logika linear. Sistem ini dengan keras kepala dan membabi buta juga mempertahankan pendapat bahwa “Allah adalah bapa(k)”.
Nilai-nilai seperti ini maupun pemahaman eksklusif mengenai “Allah adalah bapa(k)” sangat bertentangan dengan sifat dan jatidiri Allah yang compassionate. Agar the compassionate God dapat menjadi pengalaman kita, maka kita perlu mengganti nilai-nilai dominasi dan sub-ordinasi dengan relasi kemitraan, manipulasi dengan pembebasan, kontrol dengan sharing tanggungjawab, rationalisme dengan kebijakan hati, dan logika linear dengan kesadaran inklusif. Kita juga perlu menekankan dimensi feminin dari Allah.
(3) Dimensi kultural
Dimensi ketiga ini khususnya berkaitan dengan mereka yang berasal dari kebudayaan Jawa dan yang kesadaran kultural ke-Jawa-annya masih kental. Namun, lebih khusus lagi mereka yang bermental priyayi.
Orang yang bermental priyayi menghayati pekerjaan sebagai sarana untuk mencapai kedudukan dengan segala simbolnya. Orang merasa berhasil bila mendapatkan berbagai macam gelar dan penghargaan (walaupun tanpa isi), kenaikan pangkat dengan cepat (apa pun caranya), serta berbagai macam barang yang dapat mendongkrak status sosialnya (rumah besar, kendaraan baru, HP jenis terkini, dan berbagai macam klangenan … walaupun sebenarnya tidak terlalu diperlukan).
Berkaitan dengan mentalitas seperti ini, kesalahan di dalam pekerjaan (maupun di dalam hidup) selalu dianggap ènthèng sejauh hal itu tidak diketahui oleh orang lain (khususnya atasannya) maupun tidak membuat dirinya kehilangan muka.
Mentalitas seperti ini akan menghalangi diri kita untuk dapat mengalami kasih-kerahiman Allah. KerahimanTuhan justru kita rasakan, bila kita berani menghadap Dia tanpa harus memakai berbagai macam accessories serta dibarengi dengan kejujuran untuk berani mengakui segala kesalahan, dosa, dan keremukan diri kita,. Itulah yang dulu menjadi pengalaman Ignatius sendiri saat menata hati sepanjang tinggal menetap di Montserrat dan Manresa.
Mentalitas pegawai sangat bertentangan dengan pemahaman Ignatius mengenai karya sebagai keikutsertaan dalam melaksanakan karya keselamatan Allah.
(4) Berkaitan dengan pola hidup yang kita pilih
Mengimani Allah yang diimani oleh Ignatius berarti mengimani Allah yang berpihak pada kaum tersingkir. Hal ini akan membawa kita untuk memilih pola hidup miskin: berani men-share-kan apa yang kita miliki dan bahkan hidup kita sendiri, agar tidak ada lagi orang yang hidup serba kekurangan.
Iman seperti ini juga menuntut agar mereka yang dianggap sebagai sampah kita perlakukan sebagai manusia sang citra Allah. Dengan demikian, akan semakin banyak orang dapat memiliki hidup secara manusiawi (bdk. Yoh 10:10). (Selesai)