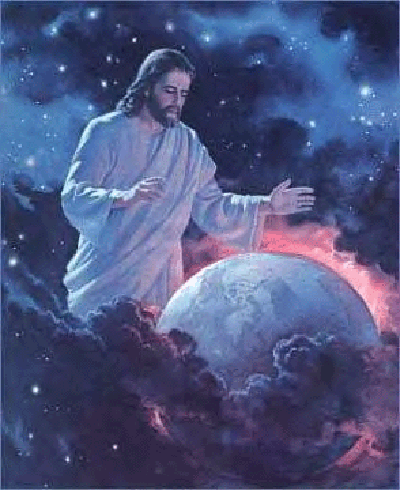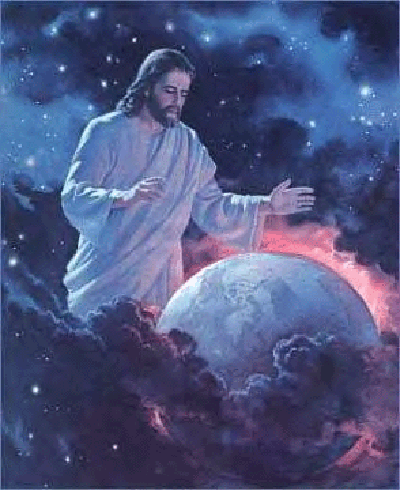 Akar dosa itu cuma dua, yakni iri hati dan sombong. Artinya, betapa sulit sekali manusia melepaskan diri dari dua hal ini. Karena iri atau sombong, kita sering menghalangi Tuhan berkarya di dunia. Kita sendiri tidak mau menjalani, tetapi orang lain tak boleh melakukan. “Sirik tanda tak mampu”, kata orang muda. Mengapa?
Akar dosa itu cuma dua, yakni iri hati dan sombong. Artinya, betapa sulit sekali manusia melepaskan diri dari dua hal ini. Karena iri atau sombong, kita sering menghalangi Tuhan berkarya di dunia. Kita sendiri tidak mau menjalani, tetapi orang lain tak boleh melakukan. “Sirik tanda tak mampu”, kata orang muda. Mengapa?
Di rumah
Dengarlah cerita ibu-ibu. Kecuali seru, biasanya berintikan bualan bahwa dirinyalah yang paling ‘hebat’. Asalnya sih, dari kodrat wanita, demi melindungi anaknya, tetapi akhirnya adalah ungkapan ketidakrelaan orang lain lebih baik.
Mungkin juga itu naluri wanita yang tak mau ditandingi, dibandingkan dengan orang lain. Kalau saja hal itu, mendominasi suasana di rumah, tentu anak-anak belajar untuk tidak rela bila orang lain lebih baik. Akibatnya tentu terbawa sampai dewasa.
Dia dapat menjadi orang yang suka menghalangi Tuhan bekerja. Dalam beberapa kasus malah terjadi demikian. Keluarga yang tinggal ibu saja, tanpa ayah, anak gadisnya jadi kurban: tak menikah juga. Sebab secara tidak sadar si ibu tidak rela kalau anaknya lebih bahagia, dengan punya suami. Alasannya biasanya macam-macam. Kurang ini, kurang itu dan selalu begitu. Tak pernah ada yang pas. Kalau anak perempuan tak berani meninggalkan rumah, jangan harap ia dapat menikah.
Di sekolah
Kadang kita temui ada guru yang pelit memberi nilai ulangan atau ujian. Alasannya sih biblis‚ tak ada seorang murid yang melebihi gurunya’. Padahal sesungguhnya ia tak rela kalau ada orang lain atau muridnya yang sepintar atau lebih pandai.
Perhatikan pula kebiasaan dalam “penentuan“ (bukan kompetisi murni) juara lomba antarsekolah. Konon, juaranya selalu gantian, antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau tahun ini juaranya sekolah swasta, tahun depan harus sekolah negeri. Lha apa itu tidak menghalangi Tuhan berkarya? Bukankah anak yang rajin, pandai, sering jadi sasaran kebencian di sekolah kita? Atau cuma tak rela Tuhan berpihak padanya alias sirik saja?
Di kantor
Ada banyak kasus yang intinya sama, tak rela orang lain mendapat posisi lebih baik. Gak usah jenjang karier. Soal keturutsertaan ikut seminar (apalagi ke luar negeri) saja sering jadi alasan untuk menjatuhkan orang lain.
Kadang malah sepele. Teman kantor mendapat kesempatan tinggal di perumahan, atau kredit kendaraan saja tak rela. Tak rela orang lain bahagia. Kenapa sulit sekali membiarkan orang lain lebih sukses, lebih bahagia? Punya istri/suami lebih cakep, lebih sukses dll?
Secara corporate, hal ini mewujud dalam persaingan tidak sehat. Tak mau bersaing secara fair. “Kamu usaha aku usaha, lihat mana yang menang.“ Tetapi, yang terjadi “kamu usaha, saya usaha, maka usahamu saya matikan“, dengan cara apa pun. Tak rela company lain mendapat profit lebih banyak. Karena itu perlu etika bisnis. Lebih perlu lagi pelaku bisnis yang beriman. Are we?
Dalam agama
Biasanya lebih parah. Tilik dan perhatikanlah doa-doa pribadi yang terucap. Secara tersamar sering mudah ditangkap sikap sirik atas anugerah yang diterima orang lain. Sikap tertutup yang menjelma menjadi macam-macam aturan melarang orang/umatnya pindah ke lain agama. Tak rela Tuhan bekerja dalam dia/mereka. “Mesti lewat aku” maunya, tetapi dirinya tak mutu.
Kalau tak bisa menahan umatnya menemukan Tuhannya, lalu menyerang orang itu, atau menyerang agama lain. Hal ini terjadi dalam semua agama. Kalau tidak tidak ada konflik antaraagama. Barangkali masalah kebebasan agama di negeri kita, mungkin juga bukan masalah agama, tetapi cuma masalah sikap/kebiasaan yang lahir dari ketidakrelaan Tuhan bekerja dalam orang lain ini ? Konkretnya menjadi tak rela agama lain lebih banyak pengikutnya dari agamaku. Karena itu menjelma menjadi perilaku menjelek-jelekkan oarang /agama orang lain.
Namun jangan salah. itu bukan hanya masalah antarpemeluk agama. Sebab hal itu juga terjadi dalam interen agama. Di Katolik misalnya saya tahu, masih saja hidup fanatisme parokial. Bukankah ini intinya sama, tak rela paroki lain lebih maju. Tak rela Tuhan bekerja di sana, di paroki lain? Kenapa tak berusaha agar Tuhan bekerja di parokiku saja? Boro-boro begitu, alih-alih refleksi, lebih mudah ‘menyerang’ pihak lain saja. Apa itu kristiani, lain soal.
Dalam masyarakat
Dalam skala nasional, hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab negeri kita ini tak pernah maju. Selalu usreg, udreg-udregan antarsuku, antargolongan, antarangkatan, antardepartemen, antarbiro, antarpartai, bahkan antarfraksi, antarmenteri. Intinya satu : tak pernah rela kalau pihak lain lebih baik, lebih maju, lebih ‘basah’, lebih inovatif.
Kalau begitu jelas bukan, tak ada tempat untuk memikirkan, apalagi mengusahakan kesejahteraan umum di negeri ini, apa pun undang-undang dan sistem pemerintahanya. Masalah laten, korupsi, mafia peradilan pun dapat dilihat dalam kerangka sikap ini : tak rela orang mendapat rejeki, upeti, whatever lah dan aku tidak.
Maka dapat dibayangkan prinsip ini: kalau dia dapat, aku juga mesti dapat lebih banyak. Kalau dia berhasil menggasak harta negara, harta rakyat, akau pun harus demikian, malah lebih besar lagi, lebih gila lagi. Celakanya, di jaman reformasi ini, nafsu demikian justru tak terbentung. Tak ada lagi batas, tembok atau tanggul yang tegas dan jelas menghalangi berlangsungnya proses bencana penghacuran bangsa ini.
Refleksi
Apa sih sulitnya membiarkan Tuhan bekerja dalam orang/komunitas lain? Kalau memang Tuhan lebih berkenan kepada mereka ya biar saja. Malah dapat menjadi pemicu untuk mawas diri. Atau tidak percayakah kalau Tuhan memberi cukup untuk diri kita? Kalau bukan iman, apalagi yang dapat membendung bencana hidup kita. Agama rupanya tak mampu menahan lagi. Jangan sampai Tuhan berkata: “Kamu memegang kunci, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, tetapi orang lain yang mau masuk kamu halangi.“