Spirit Kerjasama Kemitraan Lembaga Gereja Katolik bagi Kemanusiaan Berdasarkan “Deus Caritas Est”
SEANDAINYA tanpa pernah menerbitkan ensiklik Deus Caritas Est (selanjutnya disingkat DCE) bertepatan dengan Natal 2005, bisa jadi Kardinal Joseph Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus XVI pada April 2005 bakal tak punya pamor segemilang pendahulunya: mendiang Paus Johanes Paulus II, ‘Paus Abad Ini’. Legacy sekaligus legitimasi seorang pemimpin Gereja Katolik Sedunia sefenomenal Paus Johanes Paulus II yang sedemikian mendunia itu sehingga bahkan ketika pemakamannya pun, kerumunan orang sudah meneriakkan santo subito (kurang lebih berarti: segera saja digelari santo).
Paus dengan masa pontifikat ‘salah satu yang terpanjang’ (1978-2005) yakni hampir genap 27 tahun ini, sungguh merupakan ‘pesona dunia’, terutama bagi kiprah kemanusiaan, bukan hanya bagi Gereja Katolik.
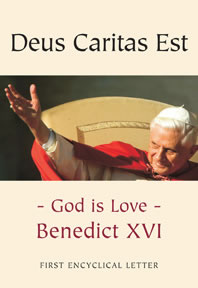
Oleh karena itu, bagi Benediktus XVI, jejak-jejak Johanes Paulus II memang bisa saja menenggelamkan karakter kepemimpinannya selama masa pontifikat yang hampir pasti bakal terbilang pendek. Jangan dilupakan: ada perbedaan usia 20 (duapuluh) tahun ketika masing-masing ‘naik tahta’ sebagai Paus: Kardinal Karol Woytila menjadi Johanes Paulus II (1978) pada usia 58 tahun, sementara Kardinal Joseph Ratzinger menjadi Benediktus XVI (2005) pada usia 78 tahun.
Akan tetapi Joseph Ratzinger bukan seorang Kardinal biasa. Kecuali terkenal brilyan dari dunia akademis, bertahun-tahun ia adalah penanggungjawab utama ajaran iman Katolik pada departemen khusus Pro Doctrina Fidei di lingkungan Vatikan. Ia merupakan ‘otak’ di balik gagasan dan penampilan menakjubkan Sri Paus Johanes Paulus II.
Tak pelak ensiklik pertama Benediktus XVI, DCE, segera sungguh mencengangkan warga Gereja Katolik sedunia dan para pemerhatinya. Sedemikian bernas dari hampir semua aspek, DCE sungguh ‘merebut hati dunia’ yang semula memprediksi Benediktus XVI bakal tak sepopuler pendahulunya.
Konteks
Izinkan saya men-sharing-kan ‘pendalaman’ khusus DCE dari konteksnya.
Menurut hemat saya, spirit Konsili Vatikan II amat melatarbelakangi pemunculan DCE. Kalau bukan harus dipandang sebagai akumulasi aneka gagasan mengenai keterlibatan Gereja Katolik dalam karya sosial kemanusiaan, DCE harus diakui sebagai ‘rangkuman awal’ dari arah-dasar sekaligus paradigma baru Gereja Katolik berinteraksi dalam karya sosial kemanusiaan. Namun sudah barang tentu sebagai salah seorang pemikir ulung dari Vatikan II, Paus Benediktus XVI tidak bakal pernah lupa akan pencerahan aggiornamento dengan segala implikasinya yang dihembuskan oleh Konsili pembaharu tersebut.
Salah satu buah fenomenal dari Konsili Vatikan II adalah terhalaunya dari kamus Katolik adagium yang berbunyi ‘extra ecclesiam nulla salus’ (harfiah: di luar Gereja tak ada keselamatan). Adagium tersebut memang sepantasnya dipahami menurut konteks zamannya. Namun betapa menyesatkan adagium itu tanpa kesadaran baru Vatikan II yang membawa perubahan maha dahsyat bahwa sesungguhnya Gereja (Katolik) bukanlah segala-galanya.
Erat hubungannya dengan paradigma baru yang dimunculkan Vatikan II adalah konteks perubahan zaman dari awal era 1960-an. Secara singkat harus dirumuskan saja sebagai: zaman berubah, dan karena itu lembaga gereja Katolik membutuhkan menyelaraskan diri pada perubahan zaman tersebut.
Dari sinilah, saya menduga, kita mulai lebih terbiasa dengan istilah-istilah teknis dalam paham teologis yang senantiasa berkembang: dari the teaching church menuju the listening church, dan kemudian berubah menjadi the participating church, untuk selanjutnya keren dengan the witnessing church.

Perubahan zaman ini mengajarkan sekurang-kurangnya sebuah hal fundamental dalam perubahan dinamika menggereja yakni keterbukaan untuk juga mampu belajar dari pihak mana pun. Keterbukaan ini segera melahirkan ‘semangat zaman’ untuk sungguh menghargai human dignity di atas segala-galanya dalam karya sosial kemanusiaan.
Kecuali konteks perubahan zaman yang sekian signifikan dan sepertinya amat-sangat cepat, kemunculan DCE dalam bacaan saya memiliki sebuah konteks lainnya yang tidak boleh disepelekan yakni implikasi dari semua dokumen yang kita buat sebagai ‘Ajaran Sosial Gereja’ (ASG) semenjak Rerum Novarum (1891): gerak karya sosial kemanusiaan Gereja Katolik harus benar-benar melintas batas.
Konteks melintas-batas menyebabkan DCE, sebagaimana semua dokumen ASG, sesungguhnya diperuntukkan bagi ‘semua’, bukan hanya khusus bagi penganut ajaran iman Katolik. Pemahaman dari terminologi Deus (Allah) idem dito denga Caritas (Cinta-Kasih) seperti banyak dikupas DCE memperlihatkan dengan terang benderang bahwa dokumen ini melintas batas-batas benua, bahasa, kebudayaan, dan ras serta bahkan melintas batas keyakinan iman manusia.
Akhirnya, lebih dari sekedar dilatarbelakangi oleh konteks tertentu, DCE barangkali harus disebutkan muncul dari sebuah semangat melahirkan cara-pandang serta cara-bertindak baru. Memang menghadapi perubahan zaman dengan segenap kompleksitasnya membutuhkan terobosan alternatif yang memperhatikan sendi-sendi fundamental mengembangkan karya sosial kemanusiaan sebagai ‘karya kita’, ‘pekerjaan bersama’; concern, commitment, dan care serta compassion untuk semua.
Sudah pasti tidak mudah, namun spirit itu bukan tidak mungkin dijangkau dalam tindakan-aksi-karya nyata.
Barangkali keutamaan pokok yang membingkai DCE dan sang penulisnya, Benedictus XVI, adalah bahwa cinta-dan-kasih-sayang tidak boleh lagi berhenti pada wacana di awang-awang, namun harus membumi pada tindakan-tindakan kongkrit: melayani tanpa pamrih.
Paling menonjol pada DCE adalah bahwa tindakan-melayani dan pekerjaan seorang pelayan bukan lagi sekedar sikap imperatif, melainkan tindakan sekaligus aksi konstitutif. Mendalami DCE saya menjadi lebih yakin bahwa Paus Benediktus XVI bukan lagi hanya seorang konseptor ulung dengan gagasan-gagasan berbudi luhur, melainkan sungguh seorang aktor bagi aksi sosial kemanusiaan yang paling nyata.
Value (s) menjadi Virtue (s)
Seperti halnya semua ensiklik ASG, demikian pula DCE pasti ingin menonjolkan beberapa pelajaran. Perkenankan saya menampilkan pelajaran-pelajaran konkrit yang sebetulnya telah saya simak dari aneka ensiklik ASG, namun menjadi juga semacam benang merah DCE.
Pelajaran ataupun pesan itu tentu merupakan nilai-nilai (values) dalam pemahaman kognitif. Akan tetapi nilai yang dihayati secara kognitif tersebut, pada hemat saya, harus segera mewujud dalam tindakan sebagai keutamaan hidup (virtues). Dengan demikian, dalam pandangan saya, nilai-nilai (values) baru sungguh bermakna bilamana terwujud dalam tindak-tanduk sebagai keutamaan (virtues).
- Pertama dan terutama; rasa hormat dan penghargaan terhadap orang miskin dan kemiskinan. Tanpa cita-rasa hormat yang mendalam terhadap kaum miskin dan problematikanya, nampaknya kita cenderung selalu merasa ‘lebih’ dan demikian menempatkan ‘sesama’ dalam ‘genggaman’, menurut kemauan ‘tangan kita’. Saya berkeyakinan, para pelayan dalam karya sosial kemanusiaan hadir, justru karena kehadiran eksistensial orang miskin dalam aneka wajah kemiskinannya. Saya berpendapat, janganlah fenomena ini diputar balik, lantaran kita bisa terjerumus pada tindakan-tindakan yang –barangkali secara tidak sadar atau tidak sengaja- justru melestarikan eksistensi orang miskin dan kemiskinannya. Menghargai orang miskin dan kemiskinan adalah sama halnya dengan berperilaku: ‘seandainya saya-lah si miskin itu’. Dengan kata lain, memakai takaran kemapanan eksistensial ‘kita’ terhadap orang lain ‘bukan kita’ hanya bakal tetap sungguh menaruh rasa hormat serta penghargaan terhadap sesama lantaran alter ego, juga super-ego kita begitu menggoda.
- Pelajaran atau pesan pertama dan terutama tersebut di atas segera membawa pada keyakinan akan equal partnership pada manusia-manusia yang sesungguhnya saling mengandaikan dan saling membutuhkan. Partnership atau kemitraan, pada hemat saya, selalu harus dengan sikap perilaku equality alias kesejajaran. Kemitrasejajaran niscaya bukan hanya mengandung nilai-nilai: kerelaan tulus bin ikhlas, kejujuran tanpa pamrih, melainkan juga menjadikan manusia polos tanpa embel-embel apa pun: bertindak, karena memang sebuah tindakan pada saat tertentu itu harus dilakukan. Kemitrasejajaran pun semestinya meyakinkan para pelayan karya sosial kemanusiaan bahwa ambisi, pretensi, dan asumsi bisa saja melencengkan atau membelokkan niat baik membantu sesama menjadi seperti sebuah kesombongan.
- Pelajaran ketiga sesungguhnya berkaitan dengan revolusi mental yang dalam rumusan mendiang Pastor Anthony de Mello SJ kurang lebih berbunyi: banyak orang berpikir untuk mengubah dunia, namun hanya sedikit yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri terlebih dahulu.

Nampaknya bermunculan para ‘pahlawan kesiangan’ dalam karya sosial kemanusiaan dengan kecenderungan yang mencuat: tidak bertahan lama, karena sudah hampir layu sebelum berkembang.
Sebagai semacam kesimpulan serba singkat untuk menutup uraian ini, DCE kiranya meyakinkan kita semua bahwasannya karya sosial kemanusiaan merupakan pekerjaan raksasa sepanjang masa. Apakah karya sosial kemanusiaan itu mesti memiliki fokus dan perspektif tertentu yang bersesuian dengan zaman dan kebutuhan zaman, tetaplah karya sosial kemanusiaan mana pun bertujuan mengangkat harkat martabat kemanusiaan.
Selanjutnya, secara khusus menyangkut implikasi DCE bagi karya sosial kemanusiaan, apakah hanya harus dengan konteks aggiornamento Vatikan II dan lain-lain sebagaimana disebutkan di atas, karya sosial kemanusiaan itu bagaimana pun juga tetaplah merupakan karya Ilahi, semenjak Allah tetap membutuhkan kita semua untuk melampiaskan cinta-dan-kasih-sayang-Nya yang tak pernah berujung.
Yogyakarta, 28 Mei 2015
Makalah ini dibawakan sebagai ‘input’ dalam pertemuan tahunan KARINA Keuskupan pada tanggal 28 Mei 2015 di Wisma Syantikara, Yogyakarta.









































