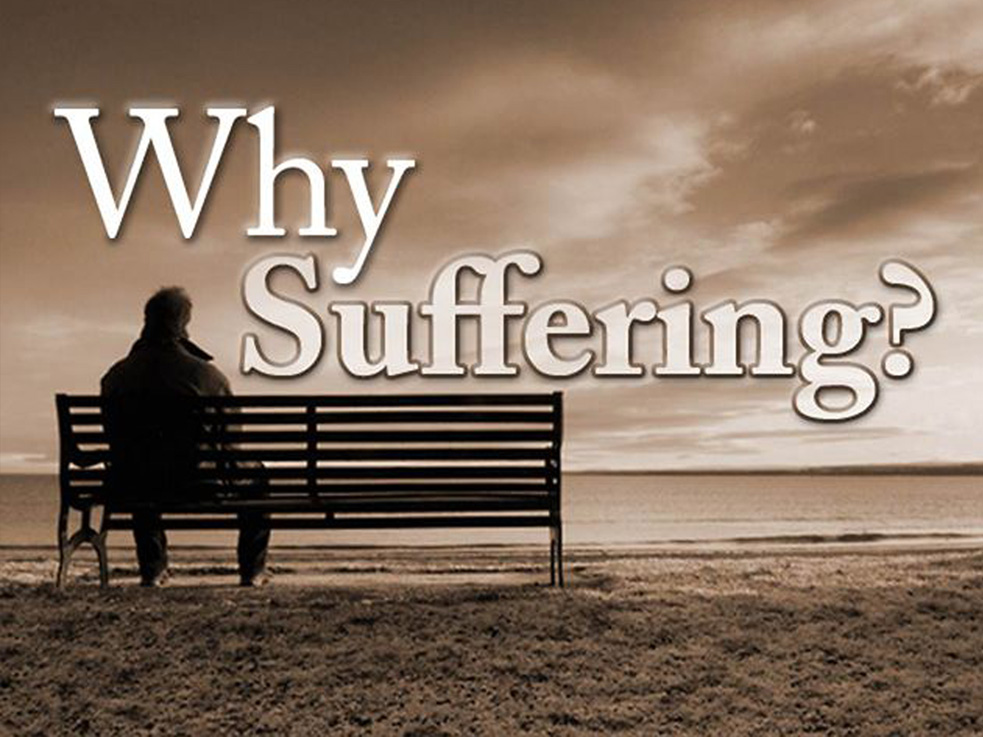SENGSARA dan penderitaan mendatangkan kesedihan. Pilu yang disebabkannya kerap kali tiada tara. Masuk akal, bahwa orang menolak dan menghindarinya. Apalagi mereka yang melihatnya sebagai pengalaman negatif belaka.
Benarkah sengsara dan penderitaan itu negatif saja dan mesti dihindari? Bagaimana dengan penderitaan para ibu saat melahirkan anaknya? Siapa yang akan mempertahankan eksistensi umat manusia jika mereka mogok melahirkan karena tidak siap menderita?
Karena sengsara dan penderitaan itu bermakna, masih ada orang yang secara rela menyongsong dan mengalaminya. Terlebih tatkala penderitaan itu menghantar orang untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi.
Bukankah para orangtua rela menderita demi keberhasilan anaknya?
Seorang kudus bernama Polikarpus juga adalah satu di antaranya. Dia rela mati demi iman dan kesaksian akan Yesus yang telah mencintai dan menyelamatkannya. Mendekati kemartirannya, tanpa mau menyangkal imannya, dia berkata:”Delapan puluh enam tahun aku mengabdi Kristus, tak pernah Ia menyakiti aku sedikitpun juga. Bagaimana mungkin aku mengutuk rajaku, yang menyelamatkan daku?”.
Pengalaman dicintai menjadi kekuatan besar untuk menanggung sengsara dan derita.
Kini sebagian umat manusia menanggung penderitaan akibat kemiskinan, ketidakadilan dan perilaku negatif lainnya. Itu situasi yang tidak ideal. Perlu dibenahi secara tepat dan bijaksana. Upaya menghapuskannya dengan kekerasan seperti memobilisasi dan manipulasi massa bukan langkahnya.
Penderitaan memang sulit dihapuskan dengan kekerasan. Bukankah kekerasan pada dirinya sendiri berpotensi melahirkan penderitaan? Pengalaman akan cintalah kekuatan sejati untuk menanggung dan menghadapi penderitaan.
Masih adakah cinta di tengah penderitaan pada zaman sekarang ini?