
ORANG awam tak banyak tahu apa dan bagaimana ranah jurisdiksi Hukum Pertanian.
Untuk mengulik perkara strategis dan maha penting ini, Titch TV sengaja mendatangi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung: Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro SH.
Hukum Pertanian beda dengan Hukum Agraria
Dari sesi ngobrol panjang lebar di rumahnya yang sejuk dan tenang di akhir Juli 2022 lalu, ternyata menjadi jelas bahwa Hukum Pertanian itu sangat berbeda dengan Hukum Agraria (Agrarian Law).
Di negara-negara maju, demikian kata Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro SH, Hukum Pertanian sering disebut Agriculture Law.

Dan di luar negeri, tambah Guru Besar Fakultas Hukum Unika Parahyangan Bandung ini, studi serius mengenai Agriculture Law itu juga sudah sangat jamak dilakukan dan berkembang sangat maju.
“Studi tentang Agriculture Law ada antara lain di Universitas Wageningen di Negeri Belanda, di Arkansas (Amerika Serikat), di Inggris, dan di Australia,” terang alumnus Seminari Mertoyudan tahun masuk 1969 ini.
Di Indonesia, jelasnya, pengertian Hukum Pertanian sering kali menjadi salah kaprah dengan Hukum Agraria. Padahal, ranah pengertiannya dan cakupan jurisdiksinya jelas sangat berbeda.
Mengatur dan melindungi petani kecil
Yang namanya hukum, kata Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro SH, tentu saja fungsi utamanya adalah mengatur.
Namun tidak hanya itu saja, karena hukum juga punya fungsi penting lainnya yakn melindungi.
Dalam konteks Hukum Pertanian, maka yang diatur adalah tata kelola pertanian sekaligus melindungi kepentingan para petani.
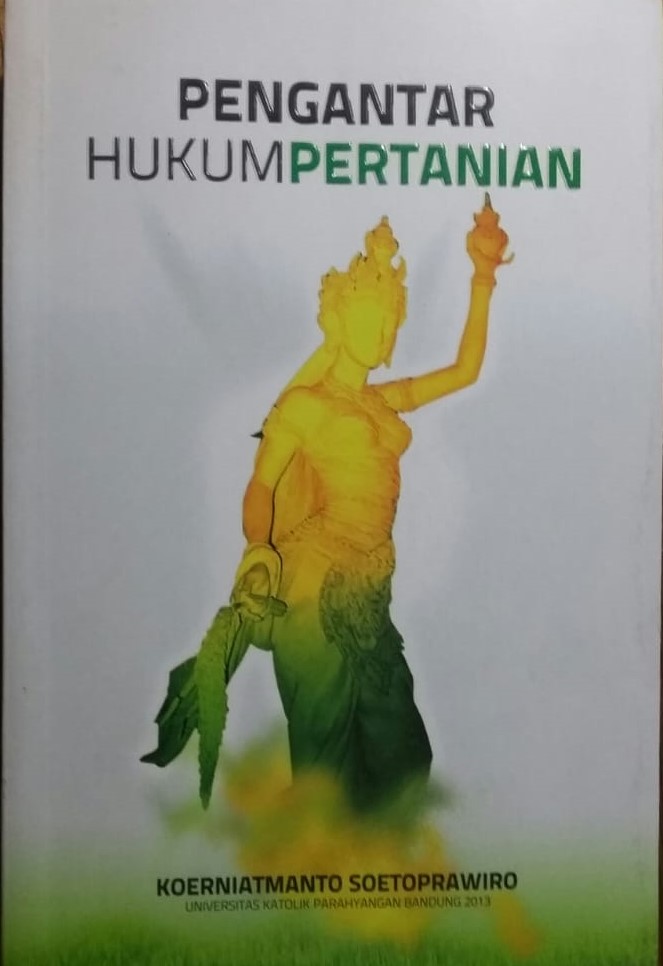
“Yang sebaiknya kita perlu cermati adalah fakta ini,” kata Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro SH, “bahwa, mayoritas pelaku produksi hasil pertanian tradisional di tanahair Indonesia adalah para petani kecil.”
Mereka ini layak diisebut petani kecil, karena areal lahan tanah garapan mereka -apakah itu tanah ladang atau sawah- juga sangatlah kecil.
Ensiklik Mater et Magistra (1961)
Lebih menarik lagi, jelas professor hukum pertanian asal Dusun Morangan di Klaten ini, ternyata Gereja Katolik Universal sudah sejak lama punya perhatian besar terhadap nasib para petani kecil.
Itu diawali dengan terbitnya Ensiklik Mater et Magistra (artinya: Ibu dan Guru) besutan Santo Paus Johannes XXIII tanggal 15 Mei 1961 – jauh-jauh hari sebelum Konsili Vatikan II berlangsung.
Lahirnya ensiklik itu dipicu oleh keprihatinan Vatikan atas fakta terjadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin yang ada di kawasan “Dunia Ketiga”.
Mater et Magistra merupakan ensiklik ke-4 besutan Paus Johannes XXIII yang sepanjang hidupnya berhasil merilis delapan ensiklik.

Yang istimewa, tulis Fridus Yansianus Derong OFM, Ensiklik Mater et Magistra ini secara khusus bicara tentang masalah pertanian.
Dan inilah untuk pertama kalinya, Gereja Katolik merilis ASG resmi yang mengkaji situasi negara-negara Dunia Ketiga yang saat itu belum sepenuhnya mengalami industrialisasi.
“Salah satu perhatian besar Gereja Katolik Universal sebagaimana tercermin dalam dokumen Ensiklik Mater et Magistra adalah gagasan tentang optio preferentialis pauperibus yang berarti perhatian lebih kepada kaum miskin,” papar Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro SH.
Pesan Mater et Magistra yang dirilis Tahta Suci Vatikan itu sangat jelas. Dokumen ini merespon isu-isu yang sebelumnya pernah disitir oleh dua ensiklik sebelumnya, yakni:
- Rerum Novarum besutan Paus Paus Leo XIII (Mei 1891) tentang persoalan serikat buruh;
- Quadragesimo Anno (artinya “Tahun ke-40″) besutan Paus Pius XI tahun 1931 dengan muatan berisi ajaran tentang pembangunan ulang tata sosial dan penyesuaiannya dengan Injil.
Dengan terbitnya Mater et Magistra, maka Gereja Katolik secara resmi mulai menaruh perhatian besar akan masalah-masalah sosial yang waktu itu mulai mengemuka.
Karenanya, ensiklik ini mengawali rentetan ajaran-ajaran Gereja Katolik tentang isu-isu sosial yang kemudian kita kenal sebagai Ajaran Sosial Gereja (ASG).
Inilah serangkaian dokumen yang bicara mengenai hak dan kewajiban segenap anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama (bonum commune) – apakah itu di lingkup nasional maupun internasional.
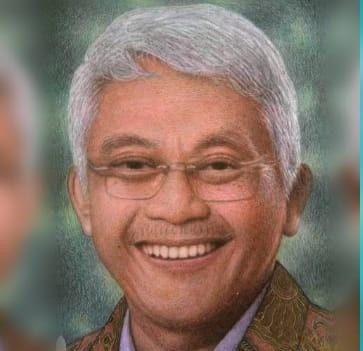
Nasib petani kecil di Indonesia
Indonesia di tahun 2022 ini memperingati 77 tahun Hari Kemerdekaan.
Setelah sekian puluh tahun dan tanpa henti telah berproses “menjadi Indonesia” ini, apakah para petani di negara kita ini sudah menikmati hasil-hasil nyata dari kemerdekaan politik pasca dideklarasikan Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945?
Titch TV mengajukan pertanyaan ini kepada Prof. Koerniarmanto Soetoprawiro SH.
Dan jawabannya sangat menohok.
Sejak dulu dan sampai sekarang, yang namanya petani kecil selalu saja “kalah” dalam pertarungan bisnis. “Karena tiga alasan,” kata Prof. Koerniatmanto.
“Yakni pertama, hasil produk pertanian itu sangat ditentukan oleh kondisi musim dan prosesnya membutuhkan waktu lama. Kalau petani mau tanam padi, paling tidak butuh waktu paling sedikitnya tiga bulan lebih baru bisa panen. Kedua, produk pertanian itu mudah busuk. Ketiga, ketidakmampuan para petani dalam posisi tawarnya untuk menjadikan diri mereka sebagai price setter atau penentu harga.”
Menemukan urgensinya
Para petani (kecil) kita selalu kalah dalam posisi tawar mereka soal penentuan harga, setiap kali berhadapan dengan para pengepul hasil pertanian – istilah lebih sopan untuk tidak mau mengatakan mereka sebagai tengkulak.
Dalam konteks yang maha luas inilah, maka urgensi mengedepankan Hukum Pertanian lalu menemukan relevansinya.
Karena di negara-negara berkembang -kalau pun itu ada Agriculture Law sudah dipraktikkan- maka cakupan perlindungan hukum atas para petani masih sangat minim.
“Kalau pun sudah ada aturan perundang-undangannya, maka jumlah UU-nya juga masih sangat sedikit,” jelas Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro SH.
Karena itu, Hukum Pertanian mesti didorong maju sebagai pelindung kepentingan petani. Juga perlu didukung agar bisa menjadi pedoman dasar untuk mengatur tata niaga atas semua hasil produk pertanian.
Tujuannya, jelas, agar para petani kita bisa hidup semakin makmur dan sejahtera. (Berlanjut)










































