DULU sekali, Gereja sering menyebutnya Sakramen ‘Pengakuan Dosa’. Namun, seiring dengan perkembangan teologi yang kian menekankan aspek kerahiman Allah, maka sejak 30 tahun terakhir ini kebiasaan orang katolik melakukan biechten yang artinya mengaku (dosa) di kamar pengakuan itu lalu disebutnya Sakramen Rekonsiliasi.
Di Kamar Pengakuan (Dosa) itulah, terjadi rekonsiliasi umat beriman dengan dirinya sendiri. Juga dia dengan Tuhan Sang Maharahim yang Maha Pengampun.
Melalui kuasa imamatnya, sang pastor memberi absolusi (pengampunan). Ini sebagai tanda silih pertobatan, maka diberikanlah penitensi (semacam sanksi) kepada umat katolik yang melakukan biechten.
Penitensi itu bisa bermacam-macam; tergantung kadar kesalahan atau derajad dosa.
Singkatnya, di Kamar Pengakuan itulah terjadi confessio (pengakuan) atas dosa dan kesalahan umat beriman.
Pengakuan itu sendiri selalu bersemangatkan rendah hati. Orang mengaku diri telah melakukan kesalahan atau dosa. Dan pengakuan itu dilakukan di hadapan seorang imam.
Pastor melalui kuasa imamatnya lalu menghadirkan rahmat Kerahiman Allah kepada peniten.
Namun, di dalam Kamar Pengakuan itu pula sangatlah mungkin terjadi kisah jalinan persahabatan yang tidak sehat. Melalui perjumpaan antar pribadi lawan jenis (baca: seorang imam yang lelaki dengan seorang umat beriman yang biechten berjenis perempuan), maka rentetan ‘dosa’ baru bisa berawal mula.
Inilah poin penting yang dengan sangat gemilang disuguhkan Paul Shoulberg, sutradara yang membesut film anyar The Good Catholic produksi tahun 2017 ini.

Bimbingan rohani
Gereja Katolik mengenal tradisi yang biasa disebut ‘bimbingan rohani’.
Inilah kegiatan pertemuan antara seorang umat katolik dengan (biasanya) seorang pastor senior yang kemampuan discretio spirituum (pembedaan roh) dan kematangan pribadinya sudah unggul, karena telah banyak makan ‘asam-garam’ melakoni hidup bakti sebagai religius.
Ini pula salah satu keunggulan tradisi Spiritualitas Yesuit (harta rohani warisan Santo Ignatius de Loyola yang kemudian sering disebut Spiritualitas Ignatian). Yakni, ketika para imam Yesuit menyediakan diri dan waktunya untuk berwawancara dengan siapa pun yang datang menemuinya untuk melakukan bimbingan rohani.
Baca juga:
- Launching Buku “Spiritualitas Yesuit dalam Keseharian”: Jadilah Peziarah Abadi (3)
- Launching Buku “Spiritualitas Yesuit dalam Keseharian”: Tuhan Ada di “Pasar” (2)
- Launching Buku “Spiritualitas Yesuit dalam Keseharian” James Martin SJ: Ramai dan Asyik (1)
- Buku Apik James Martin SJ “Spiritualitas Yesuit dalam Keseharian”, Apa itu Spiritualitas?…
- Buku Baru: “Spiritualitas Yesuit dalam Keseharian” Karya Pastor James Martin SJ dan Terbitan Yayasan…
Santo Ignatius de Loyola dan para Jesuit Perdana dikenal masyarakat sejak abad ke-15 justru karena para Jesuit itu piawai melakukan bimbingan rohani. Mereka masing-masing aktif memberi exercitia spiritualia (latihan-latihan rohani) melalui program retret bimbingan pribadi atau kelompok.
Kepiawaian itu berlangsung terus dari satu generasi ke generasi berikutnya selama enam abad kemudian dan masih eksis hingga sekarang.
Namun harus diingat bahwa tidak semua pastor Jesuit lalu boleh dianggap cakap dan mumpuni memberi retret dan latihan rohani kepada khalayak.

Di setiap kolese pendidikan Jesuit, hanya para imam Jesuit senior dengan kematangan pribadi yang teruji boleh dianggap layak menjadi seorang spiritualis bagi para frater Jesuit yang tengah menjalani formatio (pendidikan menjadi seorang Jesuit).
Di sini yang penting bukan soal pintar atau bergelar doktoral. Melainkan aspek kematangan jiwa, kedewasaan pribadi. Dan tentu saja kemampuan andal melakukan discretio (pembedaan roh) agar pastor spiritualis tersebut bisa membimbing orang lain di jalan yang benar.
Regulae tactus
Satu lagi harus dikemukakan di sini: tradisi pendidikan menjadi Jesuit sangat menekankan tradisi regulae tactus yakni serangkaian ‘aturan umum’ yang melarang para Jesuit melakukan ‘kontak fisik’ dan mengatur jarak pandang ke depan.
Utamanya, kalau ‘lawan bicara’nya adalah berkelamin perempuan. Tentu saja, maksud dari regulae tactus ini sangat mulia: jangan sampai menimbulkan greng di antara keduanya.
Dulu sekali, regulae tactus ini amat ditekankan oleh para formator Jesuit kepada para novis calon frater SJ. Karena itu, dulu sekali kita sering menyaksikan banyak para pastor Jesuit terkesan:
- Tidak mau ‘akrab’ dengan lawan bicara.
- Selalu mau mengambil jarak pandang dengan tidak mau menatap wajah dan mata lawan bicara.
- Dan tentu saja tidak mau mag-meg alias suka celamitan melakukan kontak fisik dengan lawan bicara.
- Jarak pandang menatap lawan tidak boleh –misalnya—tiga meter ke depan.
- Tidak boleh gandengan tangan.
- Tidak boleh menepuk bahu, apalagi cipika-cipiki.
Namun, sekarang tampaknya aturan regulae tactus ini semakin pudar untuk diperkenalkan dan dihayati oleh para Jesuit.
Tentu saja, Santo Ignatius de Loyola yang mencetuskan aturan itu punya maksud dan tujuan mulia.
Yakni, menjaga hubungan antarpribadi antara Jesuit dengan siapa pun tidak ‘terkontaminasi’ oleh dorongan alamiah yang muncul dari jiwa dan tubuh manusia hanya karena ada sentuhan fisik di antara keduanya.

Godaan setan selalu baik
Film The Good Catholic besutan sutradara Paul Shoulberg ini tidak bicara tentang discretio, juga tidak menyinggung soal exercitia spiritualia, dan apalagi menyinggung soal regulae tactus.
Film sederhana namun punya dimensi refleksi yang mendalam ini hanya bicara tentang tiga tipe pastor dengan karakter yang berbeda karena produksi zaman dan pola formatio yang mungkin berbeda pula.
Sangat monoton dan terkesan membosankan, karena tokoh film ini hanya memuat kisah hari-hari kehidupan ketiga orang imam itu di sebuah pastoran katolik dan kisah tentang perempuan setengah umur bernama Jane (Wrenn Schmidt), seorang penyanyi di sebuah kafe.
Setting peristiwanya hanya tiga: gereja, pastoran, dan sekilas kafe tempat Jane suka menyanyi sebagai penghibur.
Di pastoran itu, setting peristiwa hanya dua: refter (ruang makan bersama), ruang rekreasi.
Sementara di gereja, lokasi peristiwa hanya terjadi di bangku umat, altar, dan ruang biechten di mana pastor muda ganteng yang simpati bernama Father Daniel (Zachary Spicer) secara kebetulan ‘dipertemukan’ dengan Jane di bilik Kamar Pengakuan.
Jane adalah sosok pribadi yang sedikit ‘unik’. Dengan rentetan kata-kata, ia suka membombardir Pastor Daniel sehingga imam muda ini sering ‘kehabisan kata-kata’.
Puncak ‘kesintingan’ itu terjadi, ketika Jane tidak mau menerima penitensi, melainkan malah menawari dirinya sebagai sahabat baru bagi sang pastor.
Ternyata, karena kebaikan hatinya dan ingin menolong seorang peniten bertobat, maka Pastor Daniel pun tak kuasa menolaknya.
Berikutnya adalah usulan nyleneh Jane agar keduanya sudi ‘pindah tempat’: Jane boleh duduk di bilik sang pastor, sementara Pastor Daniel harus berada di bangku ‘terdakwa’ billik peninten seakan-akan ia hendak melakukan ‘pengakuan dosa’.
Maka terjadilah sedikit drama bahwa ‘proses pengakuan dosa’ itu berlangsung di kamar biechten.
Dalam sekejap, Pastor Daniel pun sadar diri bahwa ia telah ‘berjalan terlalu jauh’ keluar dari rel. Ketika ia mulai mengisahkan hal ini kepada Superior-nya (pemimpin pastoran) Father Victor (Danny Glover), sekilas tampak bahwa pembesar biara itu sedikit mencurigainya.
Jangan-jangan –demikian pikir Pastor Superior tersebut— Pastor Daniel telah melakukan ‘hal terlarang’ di Kamar Pengakuan.

Bisikan setan
Film The Good Catholic sama sekali tidak menyuguhkan adegan mesum; pun pula tak ada adegan buka baju dan apalagi badan telanjang.
Pastor Daniel juga tidak melanggar prinsip regulae tactus, sebaliknya ia telah melakukan praktik memberikan Sakramen Rekonsiliasi itu secara tertib dan benar.
Hanya saja, dengan perspektif Spiritualitas Ignatian yang mengandalkan kemampuan discretio, maka menjadi jelas di sini bahwa Pastor Daniel telah lupa bahwa “Setan” atau “Roh Jahat” –demikian menurut istilah Ignatius—dengan sangat piawai telah menggiring pastor muda itu ke ‘jalan sesat’ dengan mengiyakan permintaaan Jane yang aneh-aneh.
Yang ‘jahat’ itu bukanlah Jane, sekalipun penyanyi ini sangat obsesif dan eksentrik.
Yang ‘salah’ adalah ‘jalan pikiran’ Pastor Daniel yang tanpa sadar telah ‘kejeblos’ dalam lubang ‘sesat’ melalui niatan baik membantu orang yang hendak bertobat.
Ingat, demikian kata Santo Ignatius dalam Latihan Rohani, bujukan Setan atau Roh Jahat itu selalu bermula dari hal-hal baik dan bukan hal buruk sebagaimana biasa kita sangka.
Justru karena dilandasi niatan baik itulah, Setan lalu ‘menidurkan’ kesadaran manusia untuk kemudian sedikit demi sedikit lalu meninggalkan Tuhan dan akhirnya manusia bisa terjerembab ke dalam ‘kobangan’ dosa.
Ingat kisah Adam dan Hawa yang dibuat ‘terpedaya’ oleh bujukan Setan atas indahnya dan ranumnya Buah Terlarang yang kata Si Ular akan mampu menjadikan kedua manusia pertama itu ‘setara’ dengan Sang Pencipta.
Jadi, Setan atau “Roh Jahat” itu selalu dan akan selalu menggoda manusia bukan atas dasar nilai-nilai buruk atau jahat, namun justru dari hal-hal baik.

Dalam kasus film The Good Catholic ini, Pastor Daniel telah tergoda, karena niatan baiknya ingin menolong Jane dan godaan menuju dosa itu terjadi di bilik Kamar Pengakuan.
Suasana pra Konsili Vatikan II
Semula, Pastor Daniel dikisahkan oleh film The Good Catholic (2017) ini ingin membela diri bahwa dirinya tidak pernah ‘melakukan kesalahan’ di bilik Kamar Pengakuan.
Ia lalu membandingkan dirinya dengan Pastor Ollie (John C. McGinley), seorang imam Fransiskan yang begitu demen dengan paduan suara dan aktivitas menyanyi lagu-lagu gerejani.
Namun, sebagai seorang Superior yang sangat mumpuni, Pastor Victor bisa ‘meraba’ berkat kepekaan rohaninya bahwa di situ ada beberapa hal ‘terlarang’ yang telah dilanggar atas nama ‘kebaikan hati’.

Film itu sendiri menjelaskan hal itu. Yakni, atas nama kebaikan hati dan niatan menolong ‘jiwa’, Pastor Daniel memberi ruang dan peluang bagi Jane untuk mempermainkan makna penitensi.
Kedua, pastor membiarkan Jane ‘menyetir’ dirinya hingga terjadi ‘tukar tempat’ dan ‘tukar peran’ dalam bilik Kamar Pengakuan.
Ketegasan Pastor Superior dan otoritasnya yang begitu besar dengan gemilang telah diperlihatkan dengan sangat jelas oleh The Good Catholic ini.
Ketaatan ‘buta’ seorang pastor muda dan yunior kepada pastor senior dan pemimpin komunitas tampil begitu terang benderang. Juga ketika film ini mengupas secara filosofis-teologis tentang makna kata ‘passion’ yang menjadi bahan diskusi sengit di meja refter (ruang makan) ketika ketiga pastor beda tipe itu bersama-sama menjamu Jane makan siang.
Ingat bahwa Jane –sebagai seorang penyanyi di kafe—memaknai kata passion itu secara positif: menghidupi hal-hal yang amat disukainya dan itu membuatnya ‘hidup’. Nyanyi dan menyanyi itulah passion-nya Jane.
Namun, bagi Pastor Victor yang hidup di era pra Konsili Vatikan II –katakanlah di tahun 1950-an di kawasan Midwest Amerika seperti ditulis oleh sebuah resensi lain—kata Inggris passion juga bisa berkonotasi ‘negatif’ yakni nafsu, libido ragawi manusia.
Dan harap tahu, nafsu sering kali dicap sebagai sumber petaka.
Menjadi mahfum, ketika Pastor Ollie hanya bisa berkata terbata-bata ketika memaknai kata passion itu menurut versinya sendiri namun ditolak mentah-mentah oleh Pastor Victor.
Menjadi gelagapan pula Pastor Daniel, ketika tiba-tiba di kamar makan itu diskusi tentang passion makin memojokkan posisinya sebagai seorang pastor muda yang tanpa sadar dianggap telah melakukan kesalahan fatal. Hanya karena ia telah akrab bersahabat dengan seorang perempuan bernama Jane.
Pertemuan makan siang itu sebenarnya diharapkan bisa membuahkan ‘kejelasan’ bagi semua pihak bahwa memang tidak ada hal khusus dalam relasi pertemanan antara Pastor Daniel dan Jane.
Namun, diskusi sengit tentang makna kata passion membuyarkan harapan tersebut.
Jane pulang meninggalkan refter dengan amarah –mungkin mau mengatakan begini: “Makan tuh, passion-mu” namun tentu saja ungkapan percakapan itu tidak layak ditulis di sini.
Pastor Ollie dengan muka masam meninggalkan ruang makan. Dan yang tersisa adalah Pastor Victor dan yunior-nya Pastor Daniel.

Kini, kedua pastor beda generasi itu berada di dua ‘kubu’ berseberangan. Dan ketika berada di situ, film The Good Catholic berakhir dengan konklusi singkat.
Pastor Daniel yang suka jogging itu datang menemui Jane di rumahnya. Sesaat sebelum memasuki rumahnya, Pastor Daniel dengan muka lapang lalu melepaskan collar-nya yang menempel di leher bajunya.
Kita hanya bisa menerka tentang apa yang kemudian mungkin terjadi di rumah Jane tersebut. Bisa jadi, Pastor Daniel telah merasa diri yakin, kini saatnya ia harus melepas jubah imamnya dan kemudian memeluk mesra Jane di kamar tidur.
Itu karena ia telah menemukan dirinya sendiri. Atau -seperti bunyi anekdot para eksim (mantan seminaris)-: “Ia telah kembali ke jalan yang benar”.














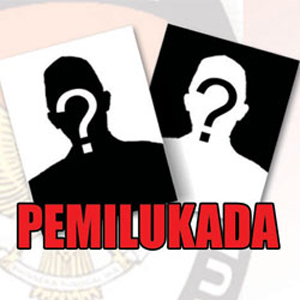




























jooos…
maturnuwuun..
Berkah Dalem
dengan segala hormat dan kerendahan hati:
biechten Mas, bukan bichten
anyway, jossss gandosss, maturnuwun kaliyan Berkah Dalem ugi…
matur nuwun pakdhe yanto
hollandsche sprekken niet
Luar biasa, bermanfaat buat kita semua untuk jadi bahan refleksi sebagai umat agar menjaga melindungi dan mendoakan para Imam dan calon Imam.
Tu est Sacredos Eternal….Itulah semboyan Imamat Kudus. Fungsi Pelayanan ditempatkan pada hic et nunc spy tdk berkembang kearah kebablasan hilang arah. Mau merefleksikan kembali flas back akan membuat semakin menghayati nilai Panggilannya…. Apa yang kamu cari???