Tak seperti tembang lawas bertitel Judul-judulan, saya pun merasa perlu memulai dengan pernyataan ini “judul di atas itu sungguh serius”.
Jadi memang bukan Judul-judulan seperti titel lagu lama besutan Orkes Dangdut Pengantar Minum Racun (PMR) yang dinyanyikan Johnny Iskandar. Melainkan sebuah judul yang saya runut dari terminologi Ignatian sebagaimana muncul dalam summary deskripsi Pater Jeronimo Nadal SJ tentang apa yang dilakukan oleh Santo Ignatius Loyola.
Menemukan Tuhan dimana-mana. Inilah terminologi khas Ignatian yang begitu populer. Atau mari kita cuplik istilah khas Yesuit yang paling asli yakni contemplativus in actione yang dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan sebagai “berdoa dalam karya”.
Catatan Jenorimo Nadal tentang “perilaku” Santo Ignatius Loyola itu pernah dikutip James Martin dalam bukunya berjudul The Jesuit Guide to (almost) Everything. Tentang Santo Ignatius di mata Nadal, James Martin lalu menulis catatan sebagai berikut:
“In all things, actions and conversations he (Ignatius) contemplated the presence of God and experienced the reality of spiritual things, so that he was a contemplative likewise in action (a thing which he used to express by saying: God must be found in everything)”
Cara kita bertindak
Nah, rasanya pantas pula kalau kita menyebut judul itu terlalu “tinggi”. Menurut saya, deskripsi Nadal tentang “perilaku” Santo Ignatius tersebut sudah sepantasnya menjadi “cara bertindak” para Yesuit.
Bahkan, saya malah berani mengatakan contemplativus in actione yang menjadi ciri karakteristik asli Yesuit harus menjadi nafas kehidupan mereka sehari-hari.
Pertanyaannya, apakah ini cocok menjadi “cara bertindak” kita? Apakah tidak terasa seperti sok, kalau kita, kaum awam berani melontarkan gagasan luhur seperti itu. Sekilas, menurut pendapat saya, “cara bertindak” khas Yesuit itu tidak cocok bagi kita.
Pendosa yang diutus
Semangat contemplativus in actione memang menjadi napas kehidupan setiap Yesuit dimana pun berada. Spiritualitas itu sungguh cocok dan relevan diamini oleh para Yesuit yang memang seratus persen mempersembahkan hidupnya bagi tersemainya “Kerajaan Allah”.
Sungguh sangat relevan menjadikan itu sebagai moto hidup bagi para “pendosa yang diutus” Tuhan sendiri untuk mewartakan Kerajaan Allah.
Istilah “para pendosa yang diutus” itu pula yang juga dikatakan Pater Provinsial SJ sekarang –Romo Riyo Mursanto SJ—saat merayakan Pesta 150 Tahun Karya Yesuit di Indonesia.
“Seluruh hidup para Yesuit adalah contemplativus in actione. Sejak novisiat, mereka dilatih harus bisa menghayati semangat spiritualitas khas Ignasian ini,” begitu kata Romo Riyo Mursanto beberapa waktu silam.
Pertanyaan nakal saya, “Apakah semangat contemplativus in actione itu masih relevan untuk kita yang tidak ada emblem Yesuit ?
Di satu sisi, kita tetap merasa sebagai “orang utusan”, namun pada sisi lain tuntutan riil hidup sebagai awam membuat kita “tak terkutik” setiap kali harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Hidup kita tentu tidak sama “ritmenya” dengan para Yesuit. Sekalipun kita pernah merasakan hari-hari hidup dalam semangat contemplativus in actione, keadaan hidup kita sekarang sudah lain. Ada tuntutan riil yang mesti kita beri atensi.
Kesempatan menghidupi “ritme rohani” itu menjadi sangat terbatas. Waktu keseharian kita sudah diserap untuk memberi atensi pada keluarga, anak, kegiatan mencari nafkah, dan menyekolahkan anak-anak.
Ini berlaku umum dan tak terkecuali bagi saya yang sudah resmi menyandang status purnawirawan pun. Kalau saja saya sengaja meluangkan waktu sedikit lebih banyak untuk kembali menjalani “ritus” semangat rohani, eh buru-buru istri sudah mulai berkomentar sinis “Sana, lebih baik kembali masuk biara saja!”
Jadi, memang akan terasa “mewah” kalau para alumni Yesuit seperti saya masih melakukan “ritme” religius seperti berdoa sebelum dan sesudah makan atau sebelum tidur, apalagi yang bukan alumni.
Menjadi lebih “wah” lagi kalau masih mau melakukan kebiasaan doa pagi dan doa malam yang oleh sebagian orang sudah layak disebut sebagai “ritme hidup” orang-orang suci di era modern ini.
Apa jadinya, kalau masih mau melakukan doa rosario? Pasti komentarnya akan lebih dahsyat lagi, termasuk ketika ada beberapa eks Yesuit masih rajin hadir untuk melakukan kegiatan rohani seperti misa dan adorasi.
Lah, saya ini Yesuit “asli” atau “aspal”? Ya terserahlah, para pembaca untuk menjawabnya sendiri.
Dikotomi hidup
Sadar atau tidak, keseharian kita yang “aspal” itu tadi tampak sebagai dikotomi antara hal duniawi dan surgawi. Apakah betul-betul sebuah dikotomi yang tak bisa diperdamaika, satu ke kiri, satunya bergerak ke kanan?
Saya punya kiat sendiri menyikapi hal ini. Selagi masih berurusan dengan hal-hal profan, ya marilah kita seratus persen fokus ke sana. Ketika kita masuk dalam ruang khalwat seperti di gereja untuk sembahyang atau mengikuti ekaristi, ya marilah kita fokuskan diri pada kegiatan rohani ini. Jangan sampai kita membiarkan diri “gagal” bertindak, lantaran ada bunyi dering atau pesan masuk kiriman dari Blackberry mengusik kita saat berdoa.
Kalau kita masih goyah dalam menyikapi “dikotomi” itu, jelaslah kalau kita pun merasa sulit menghayati semangat contemplate the presence of God sebagaimana dihayati oleh Santo Ignatius de Loyola dan diamini oleh Nadal.
Komentarnya satu, “Apa itu mungkin? Loh ternyata kok sulit?” Justru karena persoalan dikotomi itu, saya malah dibuat penasaran. Apa benar kedua “kutub” itu tak bisa diperdamaikan?
Ini sedikit sharing saya. Meski sudah puluhan tahun mundur dari Yesuit, namun toh saya masih giat juga melakukan ritus-ritus rohani seperti doa brevir, doa pagi-malam, menghadiri ekaristi, ibadat sabda, dan berdoa novena.
Dalam keseharian saya, toh ada banyak peristiwa-peristiwa sepele yang mengusik kesadaranku bahwa di situ ada kehadiran Tuhan. Tuhan menyentuh kesadaran imani saya ketika berhadapan dengan hal-hal sepele seperti berpapasan dengan iring-iringan mobil jenazah.
Spontan saya bereaksi dengan lantunan doa sederhana “Tuhan, sudilah kiranya Engkau mau ampunilah dosanya dan terimalah jiwanya di rumah surgawiMu’.
Ketika mataku terpaku pada sebuah kejadian tabrakan di depan mata, spontan saya berdoa “Tuhan, kasihanilah dia”.
Mungkin saya sendiri juga tak bisa mengingat sampai berapa kali saya melantunkan doa singkat “Terima kasih, Tuhan!”. Jangan-jangan Tuhan pun sudah mulai bosan mendengar desahan hati saya “Ampunilah aku” yang sering keluar dari mulut meski itu hanya lantunan kecil.
Nah, inilah yang paling riil dalam kehidupan rumah tangga, berantem dan konflik dengan pasangan (istri). Soal ini, saya sering mengalaminya. Sudah banyak kali, kami terlibat adu mulut, berantem sungguh-sungguh dalam artian berdebat sengit.
Tentu bukanlah pengalaman enak, apalagi di tengah debat argumentatif itu muncul kata atau kalimat yang menusuk hati. Itulah poin ketika “inti persoalan” perdebatan itu tersayat oleh kata-kata dan saya merasa sakit justru karena menyadari itu akibat kesalahanku.
Sudah pasti, kalau saya tidak melakukan apa yang disinggung istri, tentu konflik juga tidak akan muncul. Tapi ya itulah seni nakalnya laki-laki. Ketika menyadari itu akibat tindakan salah saya, justru bukan keluar kalimat “oh ya itu salahku ya?” atau “Ya, memanglah kamu ini yang benar!”.
Gengsiku terlalu tinggi untuk mengakui diri salah. Dan perdebatan sepertinya tak berujung dan susah berakhir manis.
Pertanyaan kita, apakah Tuhan hadir dalam konflik dan perdebatan rumah tangga itu? Kalau Tuhan nyata-nyata hadir dalam pertengkaran, mestinya konflik itu cepat selesai bukan? Apakah benar, Tuhan hadir persis ketika saya menyadari “ini kesalahanku”?
Mungkinkah Tuhan hadir menyadarkan aku dalam situasi menjaga wibawa dan gengsi tersebut? Kalau saya sampai berani mengatakan: “Oh ya, ini memang karena salahku!”, apakah itu tidak masuk kategori sebagai the presence of God, meski bukan dalam artian contemplate the presence of God?
Kalau Tuhan ada pada waktu terjadi pertengkaran itu, apa cepat selesai? Atau, mungkinkah tidak akan timbul pertikaian lagi? Atau, justru saat saya sadar akan kesalahan saya, di situlah Tuhan menghampiri aku dan kemudian menyadarkan aku? Apakah ini bukan the presence of God meski bukan dalam arti contemplate.
Dalam hidup berkeluarga, komunikasi dengan istri dan anak, pasti muncullah banyak insiden seperti pengalaman saya di atas. Sering kali saya harus menengadah ke atas lantaran saking jengkelnya atau karena saya pun juga tak bisa dimengerti pasangan sendiri. Sulit kiranya dalam situasi emosional seperti itu, saya bisa dengan rendah hati berani minta maaf karena telah menyakiti dia.
Nah, begitu saya berhasil “lolos” dari emosi pribadi ini, maka entenglah saya bisa mempersembahkan kepadaNya semua kekhawatiran, kejengkelan, derita, maupun kegembiraan, kesenangan, dan keberuntungan selama hidup berkeluarga. Pada saat-saat demikian ini, the presence of God itu benar-benar bisa saya rasakan.
Tapi, itu semua kan peristiwa-peristiwa yang secara personal hanya saya alami dan saya hadapi sebagai kembang-kembang penghayatan spiritualitas pribadi. Nah, yang ingin saya persoalkan di catatan ini adalah sebagai berikut.
Apakah spiritualitas Ignasian ini bisa kita terapkan sebagai suatu komunitas masyarakat atau keluarga? Dengan kata lain, mungkinkah the presence of God bisa dihayati bersama dalam keluarga?
The presence of God itu riil, kalau kita berkanjang dalam doa bersama keluarga. Taruhlah itu seperti pergi ke gereja bersama, doa makan bersama, doa malam bersama, doa rosario, dan seterusnya.
Tapi, kalau itu terjadi dan dilakukan oleh para alumni Yesuit, oleh kita yang tidak pernah menjadi Yesuit ?
Mencari spiritualitas yang khas untuk kaum awam inilah tugas kita bersama. Artikel ini memang saya maksudkan sebagai pancingan bagi kita semua untuk memikirkan persoalan penting tersebut tetap “berdoa dalam karya.”



























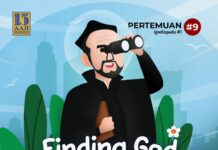















Berbahagialah bagi alumni Jesuit. Meski alumni, tentu sudah banyak bekal pengetahuan dan latihan yang didapat, yang seharusnya ‘membedakannya’ dengan para awam. Bagi kaum awam, mereka harus lebih aktif, inisiatif untuk selalu mencari, mencari dan mencari..jika ingin kehidupan spiritualitasnya berkembang. Tentu bukanlah hal yang gampang, dibutuhkan semangat, pantang menyerah. Di sisi lain, sebagai kesempatan bagi Rohaniawan ataupun alumninya untuk membagikan pengalamannya, kelebihannya kepada para awam jika mereka tidak terlalu sibuk dengan urusannya sendiri.
terima kasih tanggapannya Mbak Nina
kok baru 67 yang nge-like mas???